Ada begitu banyak hal menarik di Museum of Natural History di New York, salah satu tempat favorit yang pernah saya kunjungi (beberapa kali). Tapi ada tulisan di lobi utamanya yang sudah berulang kali saya kutip:
Learn history, use history, make history.
Belajar sejarah, gunakan sejarah, ciptakan sejarah.
Entah mengapa, kutipan itu begitu mudah digunakan untuk berbagai tulisan. Pernah untuk tulisan olahraga, pernah untuk tulisan traveling, dan sekarang saya akan menggunakannya untuk tulisan tentang pandemi.
Kita sudah berbulan-bulan hidup dalam pandemi. Ujungnya masih belum kelihatan jelas, walau mulai muncul optimisme-optimisme. Silakan ada yang berteriak sudah "hijau," tapi kenyataannya virus ini terasa "semakin dekat" di sekeliling kita. Menimpa orang-orang tak jauh dari kita, bahkan yang sudah kita kenal.
Sampai ada vaksin, yang perlu kita lakukan sangat sederhana. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak. Ini bisa meminimalisasi penyebaran virus, meminimalisasi korban, menjaga diri sendiri dan orang lain.
Sudah bukan rahasia, kampanye tiga hal sederhana itu ternyata bukan hal mudah. Rasanya tidak sedikit yang memang tidak akan menurut. Beranggapan konspirasi lah, dan lain sebagainya.
Rasanya ada yang memang tipe tidak peduli. Keluarganya barusan meninggal karena virus ini, eh, tak sampai beberapa hari sudah berkeliaran gowes bersama orang lain.
Ternyata benar, kita memang baru bisa melihat karakter orang yang sebenarnya di tengah masa sulit.
Dan sebenarnya, ketidaktaatan atau "kengawuran" ini berlaku di mana-mana. Berita-berita di Negeri Trump juga masih banyak mengulas "penolakan" pemakaian masker dan lain-lain itu.
Di negara yang mengutamakan kebebasan berpendapat itu, masih ada yang benar-benar mengartikannya sebagai "kebebasan untuk tidak peduli dan membawa bahaya untuk orang lain."
Sepertinya, hanya negara-negara yang "keras" yang mampu mengontrol dan memaksa warganya untuk taat. Sebagai buntutnya, seolah mampu melawan pandemi ini secara lebih efektif.
Padahal, pandemi ini ada sejarahnya. Seratus tahun lalu lebih sedikit (1918). Dengan flu Spanyol. Nama yang mengecoh, karena flu ini aslinya bermula di barak militer Amerika di Kansas.
Di zaman belum ada internet, belum ada lalu lintas global seperti sekarang, virus itu membunuh jutaan orang.
Sebuah artikel anyar di New York Times membuat saya terpikat, sekaligus merasakan sebuah kekonyolan. Bahwa setelah lebih dari 100 tahun, perilaku manusia ternyata masih sama. Ada internet atau tidak, globalisasi atau tidak.
Dalam artikel itu, digambarkan betapa pada 1918 dan 1919, anjuran atau aturan bermasker menjadi perdebatan publik yang sangat besar. Sampai menjadi topik besar politik. Tidak jauh dari sekarang, di saat Amerika sedang bersiap memilih presiden lagi pada November 2020 nanti.
Tulisan itu mengambil contoh kota San Francisco pada penghujung 1918, setelah pandemi berlangsung beberapa bulan (seperti sekarang). Kota San Francisco menerapkan aturan ketat, mewajibkan warganya bermasker. Ini bukan satu-satunya kota, tapi ini yang pertama yang mewajibkan warganya bermasker.
Kalau melanggar, ada denda USD 5, USD 10, atau hukuman penjara sepuluh hari. Aturan ini berlaku sebulan.
Diterapkan mulai 22 Oktober 1918, total 1.000 orang ditangkap pada 9 Novembernya. Banyak hukuman tahanan, antara delapan jam hingga sepuluh hari. Mereka yang tak mampu membayar USD 5 ditahan 48 jam.
Protes pun bermunculan. Perdebatan, pertengkaran, bahkan saling tembak terjadi gara-gara pakai masker atau tidak.
Kemudian, sebulan berlalu. Aturan wajib bermasker dicabut. Orang pun berpesta di mana-mana.
Tentu saja, korban-korban virus kembali berguguran.
San Francisco kembali mengetati aturan. Kembali mewajibkan memakai masker. Perlawanan makin keras. Ada ancaman bom bagi pejabat kesehatan kota. Muncul ormas anti-masker. Benar-benar jadi topik politik.

Karena aturan kesehatan terus mendapat perlawanan, ketika badai virus terus berlanjut hingga akhir 1919, korban meninggal karena flu itu cukup mencengangkan di San Francisco. Sebanyak 30 dari 1.000 warga San Francisco meninggal. Total yang jadi korban jiwa di Amerika mendekati angka 700 ribu.
Ah, lebih dari 100 tahun kemudian, dunia tidak berubah. Adanya globalisasi, adanya internet, adanya media sosial, ternyata tidak mengubah banyak perilaku manusia.
Perdebatan dan pertengkaran yang sama masih terjadi di era pandemi Covid-19 ini.
Ketika sempat ikut pertemuan dengan Ketua Gugus Tugas BNPB Letjen TNI Doni Monardo beberapa hari lalu, saya sempat agak tercengang dengan salah satu cerita beliau. Dia bercerita tentang pandemi flu Spanyol dan dampaknya di Indonesia.
Terus terang, saya tidak pernah mendapat penjelasan clear tentang pandemi 1918 itu di Indonesia. Mengingat pencatatan sejarah kita yang... Yah, begitulah. Kata beliau, Jawa Timur termasuk paling parah waktu itu. Bahkan beliau menyebut sepertiga penduduk Madura menjadi korban meninggal.
Sekarang, Jawa Timur memang kembali jadi zona merah.

Letjen Doni Monardo bersama Azrul Ananda dan perwakilan bonek dalam acara gerakan sejuta masker dan kampanye Tri Wani di Surabaya, 16 Juli lalu.
Tapi saya mencoba menghibur diri. Sambil mengelus dada, saya mencoba memaklumi bila orang di sini tidak bisa dengan mudah menuruti anjuran memakai masker dan protokol kesehatan lain. Alasannya? Karena sejarahnya tidak tercatat dengan baik, he he he...
Bagi saya, itu membuat kita "lebih baik" dari orang Amerika. Yang sudah jelas-jelas ada catatan sejarahnya tapi tetap tidak nurut. Wkwkwk... (azrul ananda)
Baca juga: Bonek Bagi Sejuta Masker Se-Indonesia
Foto-Foto: Vintage Space/Alamy - Chicago History Museum/Getty Images - Dokumentasi Persebaya.id
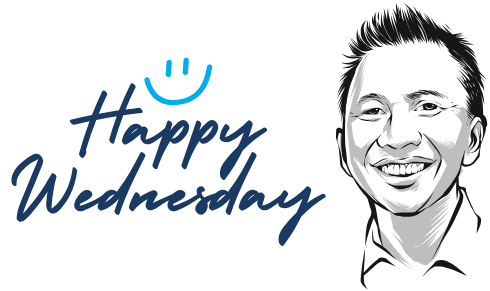












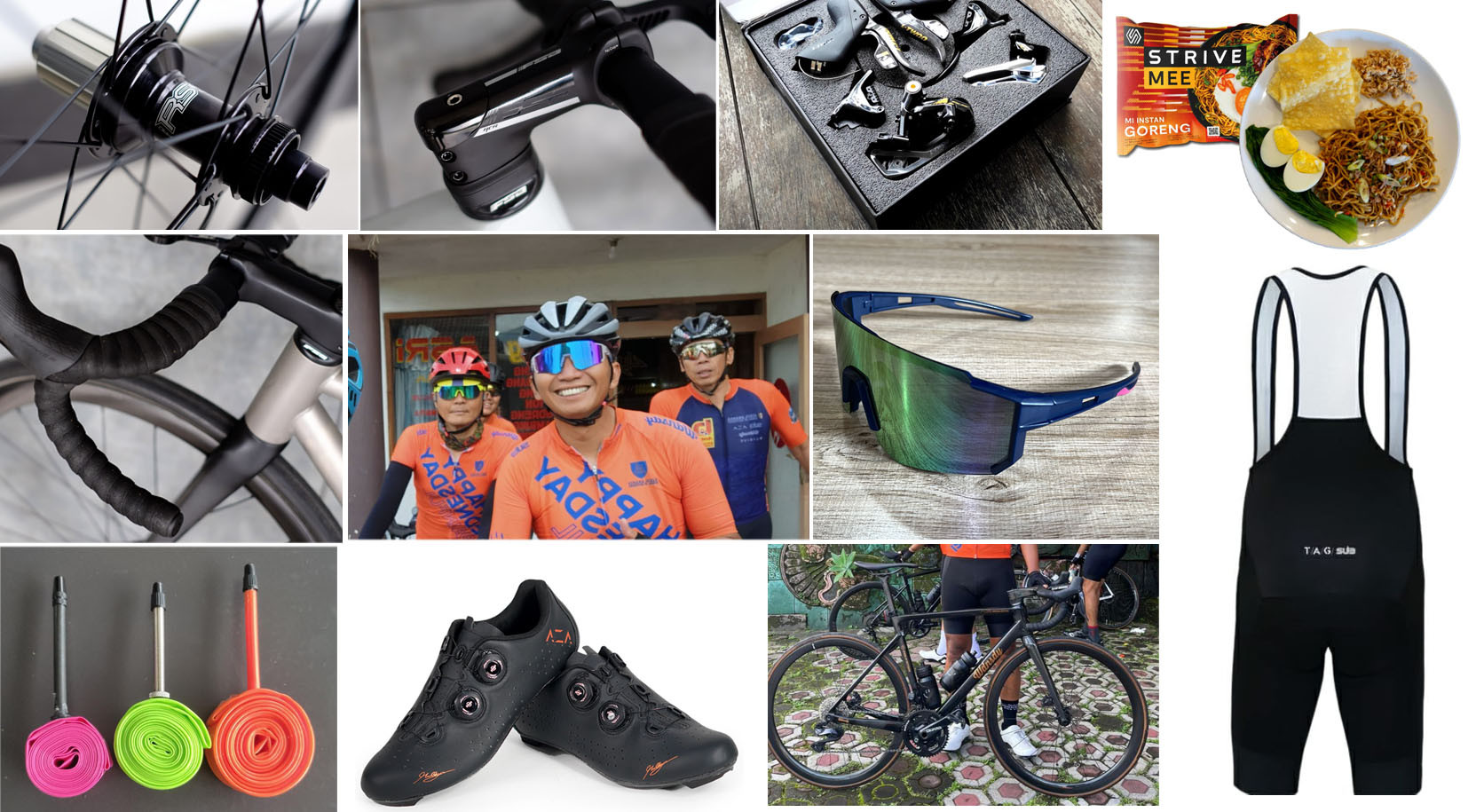


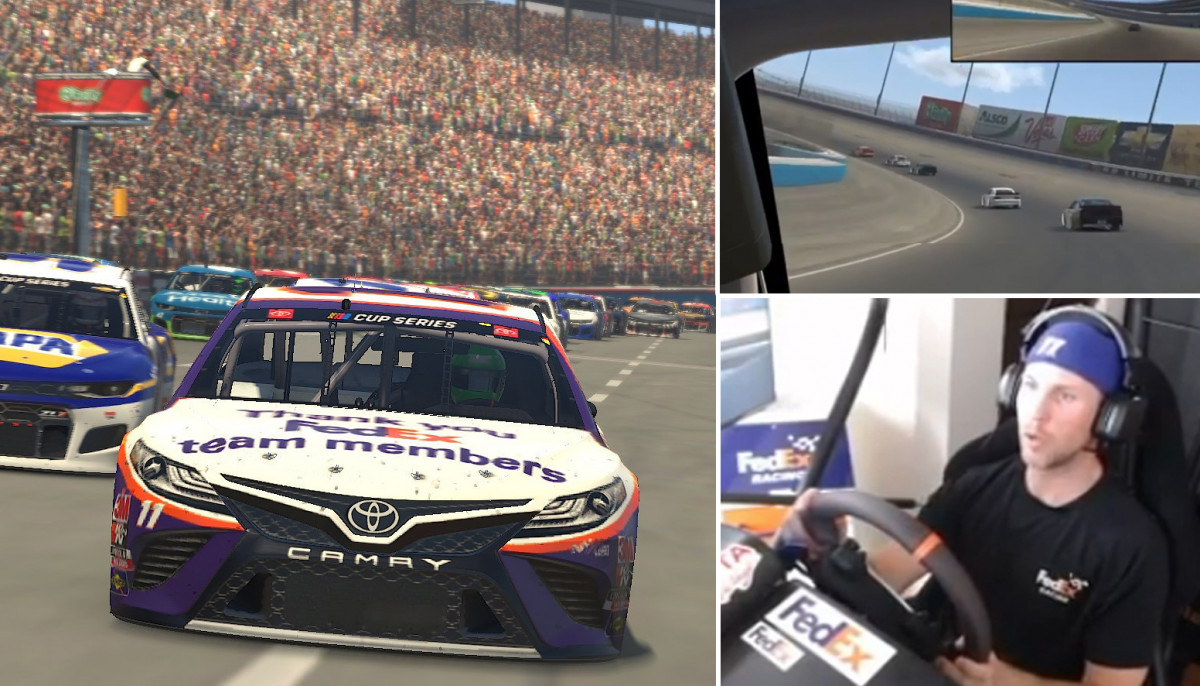

.jpg)