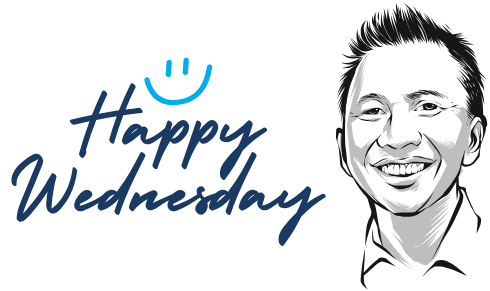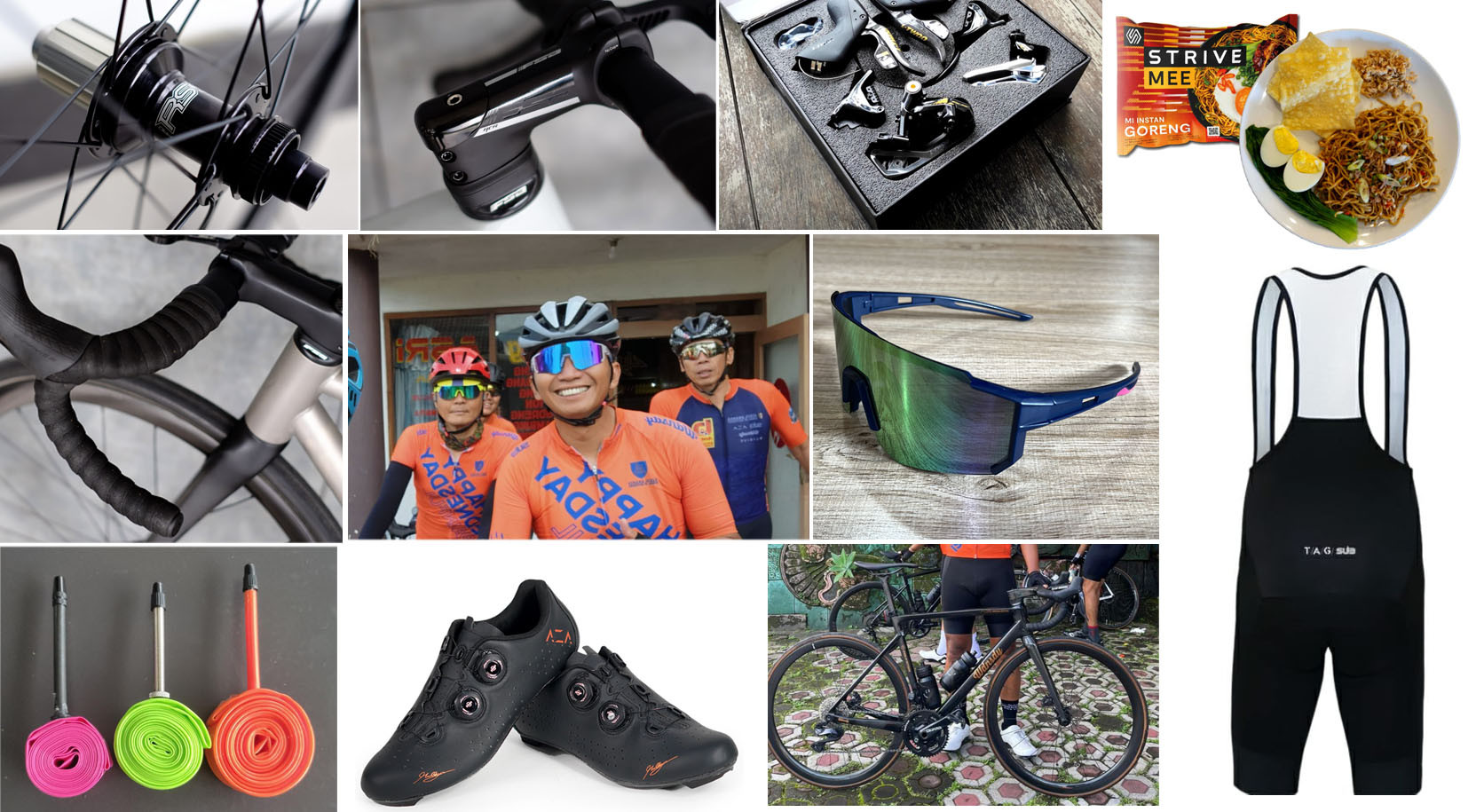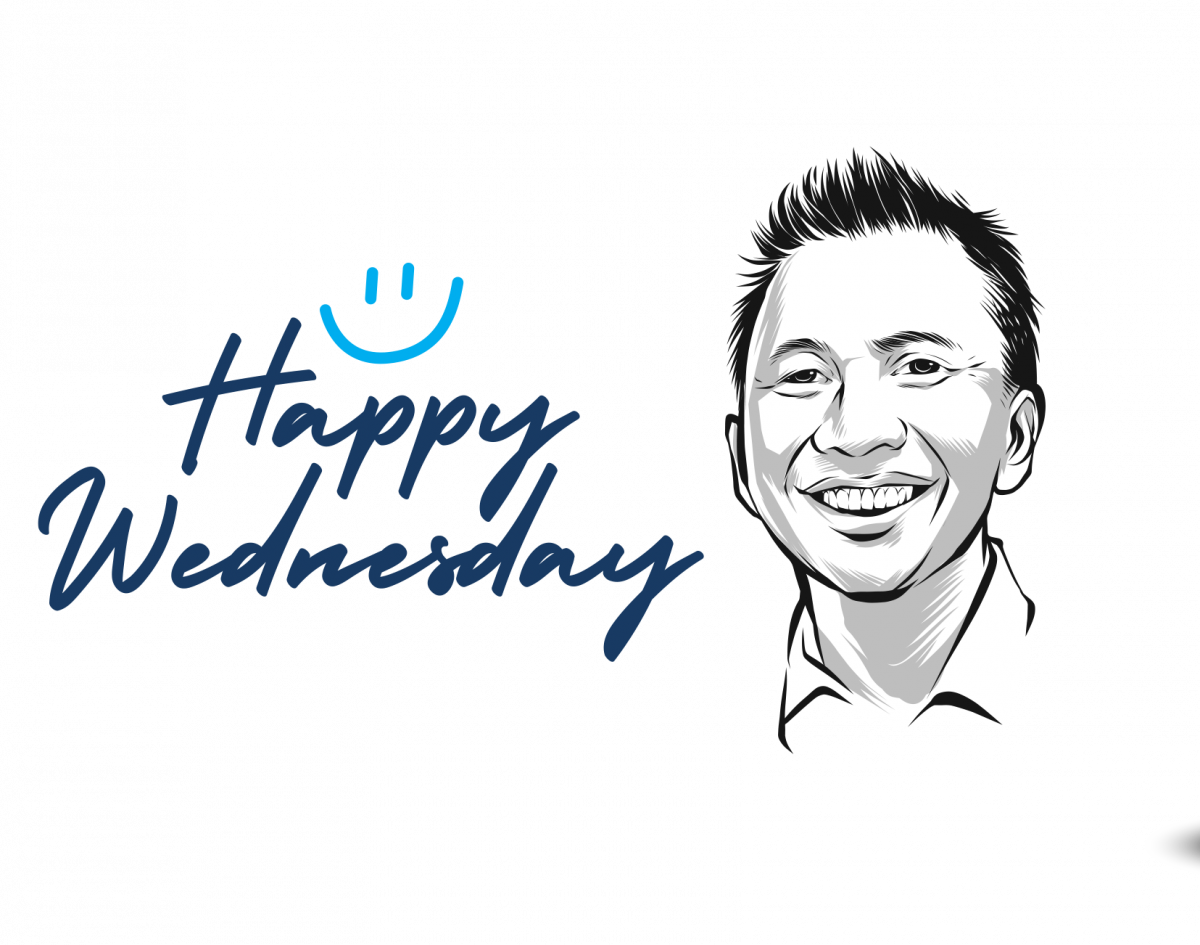Pagi itu, 12 September 2001, saya terbang ke Amerika Serikat. Untuk kembali mengunjungi teman-teman di Sacramento. Itu kunjungan saya pertama sejak lulus kuliah dan balik ke Indonesia pada Februari 2000.
Malam sebelumnya (WIB), peristiwa mengguncang dunia itu terjadi. Dua pesawat komersial menabrak gedung kembar World Trade Center (WTC) New York. Plus ada pesawat lain "menyerang" Pentagon dan satu lagi jatuh di tempat lain.
Pagi itu, saat boarding, belum ada rencana ekstrem apa-apa. Ada perasaan heboh, tapi waktu itu skala kegemparannya belum benar-benar terasa. Masih lebih banyak perasaan tak sabar segera ketemu teman-teman lagi di Sacramento.
Tentu saja, semua penerbangan ke Amerika setelah itu dihentikan. Tapi saya baru "terhadang" saat transit di Hongkong. Begitu mendarat, kami diberi tahu kalau penerbangan lanjutan (ke San Francisco) ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Saat menunggu kepastian itu, saya mendapat telepon dari Mbak Nany Wijaya, mantan jurnalis legendaris yang waktu itu direktur koran tempat saya "bermain-main" (karena memang tidak digaji). "Ulik (panggilan saya) tolong alihkan penerbanganmu ke New York. Kita butuh kamu liputan langsung dari sana," ucapnya.
Memindahkan tiket pesawat urusan gampang. Berangkatnya lagi kapan masih belum jelas. Pada akhirnya, saya menunggu dua malam di Hongkong.
Begitu akhirnya dapat kepastian terbang, segalanya jadi jauh lebih tegang. Aturannya sangat ketat. Selama perjalanan sama sekali tidak boleh keluar pesawat, termasuk saat transit di Toronto. Jadi, total saya --dan penumpang lain-- tidak keluar pesawat sama sekali selama 24 jam lebih.
Pesawat mendarat di New York pada 14 September 2001, malam hari. Di bandara saya mem-booking hotel di kawasan Midtown. Waktu itu belum gampang online seperti sekarang. Lalu saya naik taksi kuning New York yang kondang, dari Bandara John F. Kennedy ke kawasan Midtown Manhattan.
Di dalam taksi, sang sopir bertanya, saya dari mana. Saya jawab Indonesia. Dia tanya kota mana. Saya jawab Surabaya. "Oh, King Kong!" timpalnya cepat.
Saya pun heran, apa maksudnya King Kong?
Dia menjelaskan: "Surabaya itu tempatnya King Kong di film."
Usut punya usut, di film King Kong kota Surabaya memang disinggung. Mahluk raksasa itu memang berasal dari Skull Island, yang seharusnya tidak jauh dari Sumatera. Tapi, kapal yang membawanya ke New York berangkat dari Surabaya, yang dulu memang punya pelabuhan terbesar di kawasan ini.
Kalau Anda nonton film King Kong tahun 1976, maka adegan pertama langsung menampilkan tulisan besar di layar: "Surabaya." Di film buatan Peter Jackson pada 2005, kapal yang membawanya bernama "Venture Surabaya" (walau mungkin seharusnya "Soerabaia").
Saat menuju Midtown, jalan ke arah Selatan, di malam gelap itu terlihat langit oranye di kejauhan. Api masih membara di kawasan Ground Zero WTC, yang berlokasi di kawasan Lower Manhattan.
Malam itu saya masuk hotel, istirahat, karena besoknya sejak sepagi mungkin sudah harus "bekerja."
Kota New York begitu lengang. Tidak ada kereta bawah tanah beroperasi ke selatan. Semua berhenti sebelum mencapai Lower Manhattan. Saya harus jalan kaki hampir 6 km ke kawasan itu. Mampir dulu ke kantor New York Police Department (NYPD) untuk mengurus izin pass masuk kawasan tertutup. Waktu itu, hanya saya satu-satunya peliput dari Indonesia.
Waktu itu saya bawa kamera film plus kamera digital kecil (karena masih masa transisi teknologi). Bawa laptop. Walau niat liburan, sudah kebiasaan bawa semua itu ke mana-mana.
Terus terang, waktu itu akses saya terhenti sekitar dua blok dari Ground Zero. Karena situasi masih terlalu berbahaya. Itu pun saya seperti masuk zona perang. Reruntuhan berserakan, debu menutupi bangunan-bangunan.
Tapi, seperti saat melakukan liputan-liputan lain, saya selalu terpikat pada cerita-cerita manusianya. Saya ingin sampaikan, sebelum 2001 itu, saya sangat tidak suka New York. Saya punya pengalaman cukup buruk saat kali pertama pada musim dingin, akhir 1993. Waktu itu umur 16 tahun, saya ketakutan luar biasa saat menggunakan sebuah telepon umum. Bagaimana tidak, saat menelepon, tiba-tiba di sebelah saya ada orang dengan kasar mencongkel telepon untuk mencuri koin-koin di dalamnya!
Dan sudah bukan rahasia lagi, New York bukan kota yang ramah.
Semua itu benar-benar berbalik sejak 2001.
Makna dari sebuah bencana besar: Warganya jadi seperti diingatkan, dibangunkan, untuk lebih mengapresiasi hidup dan sesama. Setiap hari jalan kaki ke kawasan Ground Zero, saya selalu tersentuh oleh aksi orang-orang yang menyoraki, menyemangati, dan memberi makanan atau minuman kepada para pekerja penyelamat.
Semua taman-taman diisi orang-orang yang berdoa, menaruh bunga, menyalakan lilin. Satu sama lain jadi lebih saling menyapa, minimal dengan menundukkan kepala saat berpapasan.
Paling menyentuh saat saya mencuci film dan mencetak hasilnya di sebuah drug store (farmasi) tak jauh dari Lower Manhattan. Petugasnya tahu isi kamera saya apa. Dan pria kulit hitam itu pun bertanya, dengan wajah penuh kekhawatiran: "Apakah mereka di dalam sana baik-baik saja?"
Saya hanya bisa menjawab apa adanya. Yang saya lihat. Dan memang saya memang tidak boleh masuk sampai ke pusatnya.
Saya pergi ke kawasan komunitas Muslim di Brooklyn, dan mereka mengaku tidak mendapatkan diskriminasi. Satu-dua pasti ada, dan itu normal di mana saja. Tapi overall mereka malah merasa dibantu dan dilindungi oleh komunitas warga lain di sekitar.
Sejak saat itu, New York memang banyak berubah.
Dua tahun kemudian, atas undangan pemerintah AS, saya ke sana lagi. Melihat progres terbaru, serta rencana pembangunan di kawasan itu. Dua tahun setelah itu, saya ke sana lagi bersama istri untuk liburan. Progres pembangunannya makin kelihatan. Dan New York sudah bukan lagi kota yang menyeramkan buat saya.
Belakangan, semua mungkin tahu, New York merupakan salah satu kota yang paling terhantam oleh pandemi Covid-19.
Ini benar-benar kota yang banyak ujiannya. New York bukan hanya kota yang sering digempur segala ujian di film-film Hollywood. Ini kota yang sangat tangguh menghadapi segala siksaan nyata. Serangan teroris terbesar. Serangan virus yang tak terlihat. Semua sudah menghantamnya.
Mungkin kalau Godzilla benar-benar ada, atau mahluk angkasa luar benar-benar ada, baru nanti ada ujian berbeda lagi.
Saya belum tahu seperti apa New York setelah pandemi ini. Perubahan besar apa lagi yang terjadi di masyarakatnya. Karena yang real belum tentu sama dengan yang diberitakan. Kita harus benar-benar di sana untuk mendapatkan sense yang sebenarnya.
Semoga saja pandemi ini segera mereda beneran. Penasaran pergi ke sana lagi. Mengunjungi lagi Lower Manhattan. Tempat 20 tahun lalu saya melihat langit oranye di malam hari, dan merasakan bagaimana orang-orang "keras" bisa berubah menjadi saling peduli.(Azrul Ananda)