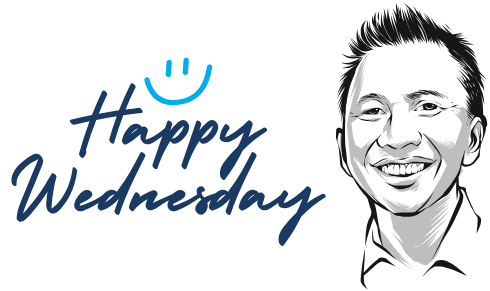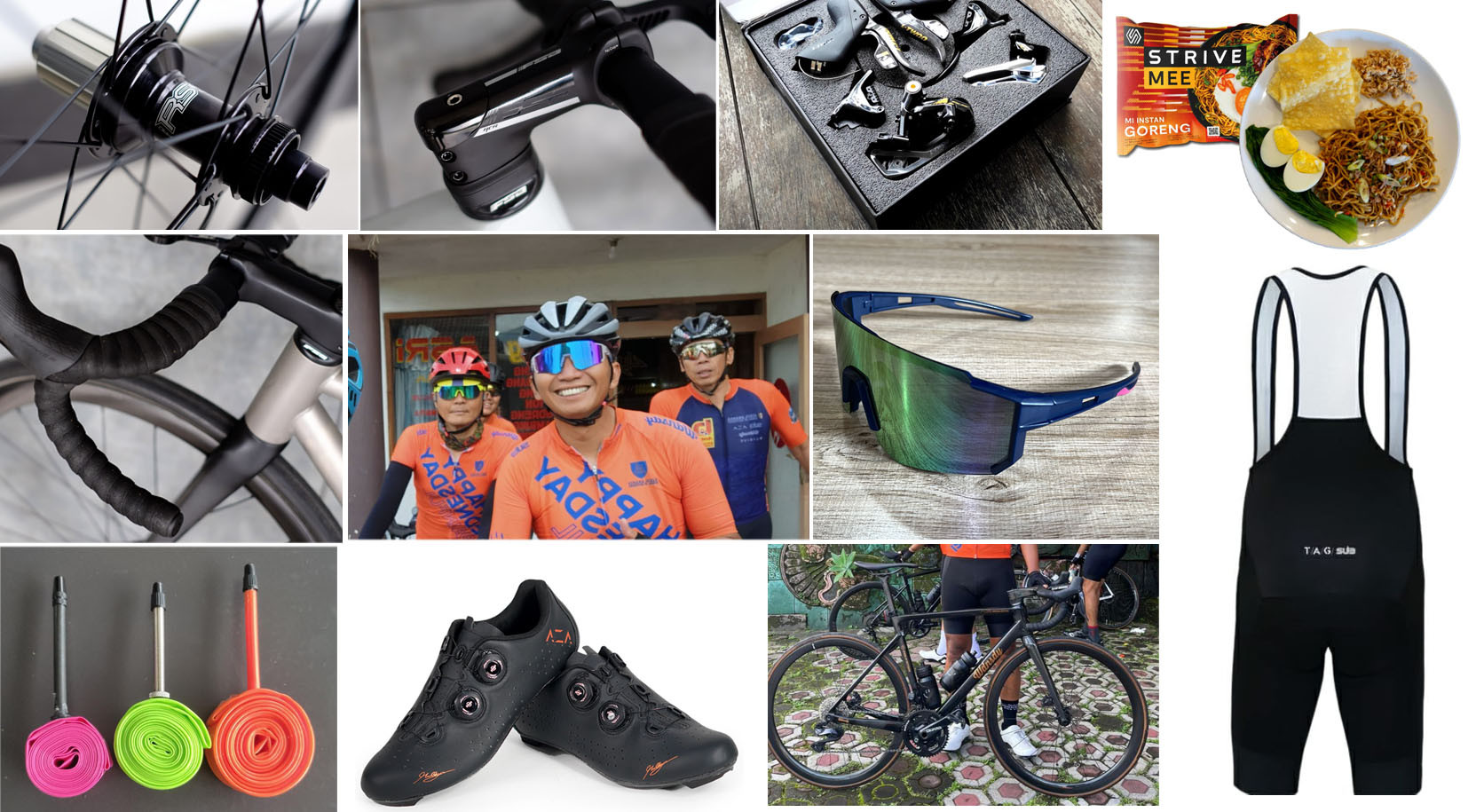Gara-gara sudah belasan tahun berkutat di olahraga, khususnya basket, saya punya kenalan banyak orang tinggi. Bahkan tinggi sekali. Ketika ngobrol dengan mereka, rata-rata punya cerita sakit saat masa pertumbuhan dulu.
Misalnya Danny Granger, mantan pemain NBA yang pernah ke Surabaya untuk melatih pemain-pemain DBL pada 2008. Pemain bertinggi badan 208 cm itu mengaku saat berusia 15 tahun adalah masa-masa paling menyakitkan. Lutut dan sendi-sendinya sering nyeri. Pada masa yang sama, tinggi badannya meroket dalam waktu singkat.
Masa-masa "growth spurts" itu sering disebut dengan istilah "growing pain." Masa-masa "menyakitkan" sebelum badan kita menjadi lebih besar dan kuat. Dan itu tampaknya terasa ekstrem bagi orang-orang yang tingginya tidak umum seperti pemain-pemain basket kelas dunia.
Karena kalau mau membandingkan, saat berusia 16 tahun, pada tahun pertama saya tinggal di Amerika, hanya dalam setahun tinggi saya bertambah 5 cm dan bobot melonjak 15 kg. Sejak saat itu tinggi saya sudah tidak bertambah lagi. Jadi, mungkin tahun itulah growth spurts saya terjadi. Tapi tidak terasa sakit he he he...
Istilah "growing pain" itu kemudian banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, pertumbuhan perusahaan, dan olahraga. Khusus untuk olahraga beregu: Momen saat sebuah tim harus menjadi padu menuju lebih kuat.
Keluarga baru harus menghadapi growing pain sebelum pasangan suami dan istri benar-benar bisa hidup bersama. Minimal, hingga benar-benar cuek dengan kekurangan satu sama lain.
Perusahaan yang membesar harus menjalani growing pain, menjalani ujian, sebelum bisa menjadi lebih besar dan kuat. Kadang, dengan konsekuensi harus mengorbankan orang-orang yang terlibat di dalamnya sejak awal.
Tim olahraga lebih seru diperhatikan, karena mereka harus menjalaninya di area yang sangat publik, di hadapan orang yang sangat memperhatikan. Khususnya mungkin pendukungnya sendiri.
Padahal, fase itu sering harus dilalui. Bahkan harus dilalui kalau ingin benar-benar teruji jadi kuat. Tidak jarang, fase itu sengaja dibuat. Untuk memastikan tim tersebut benar-benar tahan banting, benar-benar punya kemampuan, benar-benar punya ceiling (potensi atas maksimal) kemampuan yang tinggi.
Banyak tim hebat yang saya amati, di olahraga apa pun, berani memaksakan fase ini untuk naik kelas. Di atas kertas kelihatan turun grade, tapi sebenarnya mundur selangkah untuk maju dua langkah. Karena kalau tidak berubah, jangan-jangan nantinya malah jalan di tempat.
Pemain supermahal dilepas, kadang bukan melulu karena harganya. Tapi karena harga itu mungkin tidak menawarkan ceiling potensi yang tinggi. Yang penting core utama dipertahankan, "nyawa" dipertahankan, yang kemudian dipadu lagi dengan keping-keping puzzle baru yang diharapkan punya ceiling jauh lebih tinggi di kemudian hari.
Tentu saja ini teorinya. Praktiknya belum tentu mudah. Organisasinya belum tentu bisa melakukan. Belum tentu berani melakukan.
Dan yang berani dan mampu melakukan, juga belum tentu kemudian jadi berhasil. Karena itulah olahraga, itulah manusia.
Tapi ada contoh-contoh berhasilnya. Di NBA, Golden State Warriors sudah beberapa kali melakukan ini. Termasuk ketika mengawali era suksesnya dulu. Bersabar menunggu Stephen Curry tumbuh, "membuang" bintang-bintang utamanya dulu. Bahkan, tim ini berani mundur selangkah ketika bintang-bintang utamanya cedera. Hancur dulu setahun, lalu tahun berikutnya tiba-tiba dominan lagi ketika bintang lama itu dikelilingi banyak amunisi muda segar.

Tim favorit saya di NFL, Kansas City Chiefs, tahun ini melakukan itu. Wide receiver (kasarnya penangkap bola) terbaiknya dilepas, tidak mau membayar semahal tim lain. Walau banyak dihujat, merekalah yang lebih tahu plus-minus pemain tersebut dari dalam. Banyak hal-hal yang tidak bisa diungkapkan ke publik.
Sebagai gantinya, Chiefs mengelilingi bintang quarterback Patrick Mahomes dengan sederetan wide receiver lain yang muda-muda. Setelah dua pertandingan pramusim, tim ini tiba-tiba dianggap sebagai unggulan utama lagi. Dan prospek tim ini (ceiling) tiba-tiba kelihatan lebih tinggi lagi.
Dan olahraga di Amerika itu harus melakukan keberanian-keberanian itu di hadapan penonton/penggemar yang sangat pintar. Harus mampu membuat kagum pengamat-pengamat yang sangat pintar (seringkali gaji pengamat di atas gaji pelatih, karena mereka background-nya juga pelaku manajemen, pelatih, atau pemain).
Saya ingin mengutip omongan Colin Cowherd, seorang pengamat olahraga yang saya sukai talk show atau podcast-nya. Dia membuat kesimpulan tentang kunci membangun sukses berkepanjangan di sebuah tim NFL.
Satu, harus punya quarterback bintang yang berkomitmen untuk menang.
Quarterback itu playmaker. Dia harus punya kelas beneran sebagai fondasi utama sebuah tim. Kalau belum punya, harus terus mencari! Jangan terpaksa menerima yang "bintang tanggung," tak peduli apa omongan orang.
Dua, "Value your players, but don't fall in love."
Hargai, hormati, dan rawat pemain-pemainmu sebaik mungkin. Tapi jangan sampai jatuh cinta. Wah, di Indonesia ini banyak kejadiannya...
Tiga, pelatih kepala yang hebat.
Kalau bisa memenuhi tiga itu, maka sustainable success akan tercapai. Kalau belum bisa memenuhi, jangan takut untuk selalu berproses, jangan takut untuk menjalani terus growing pain... (azrul ananda)