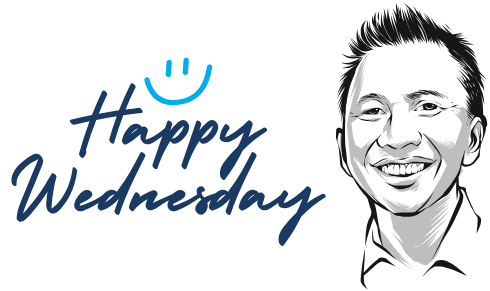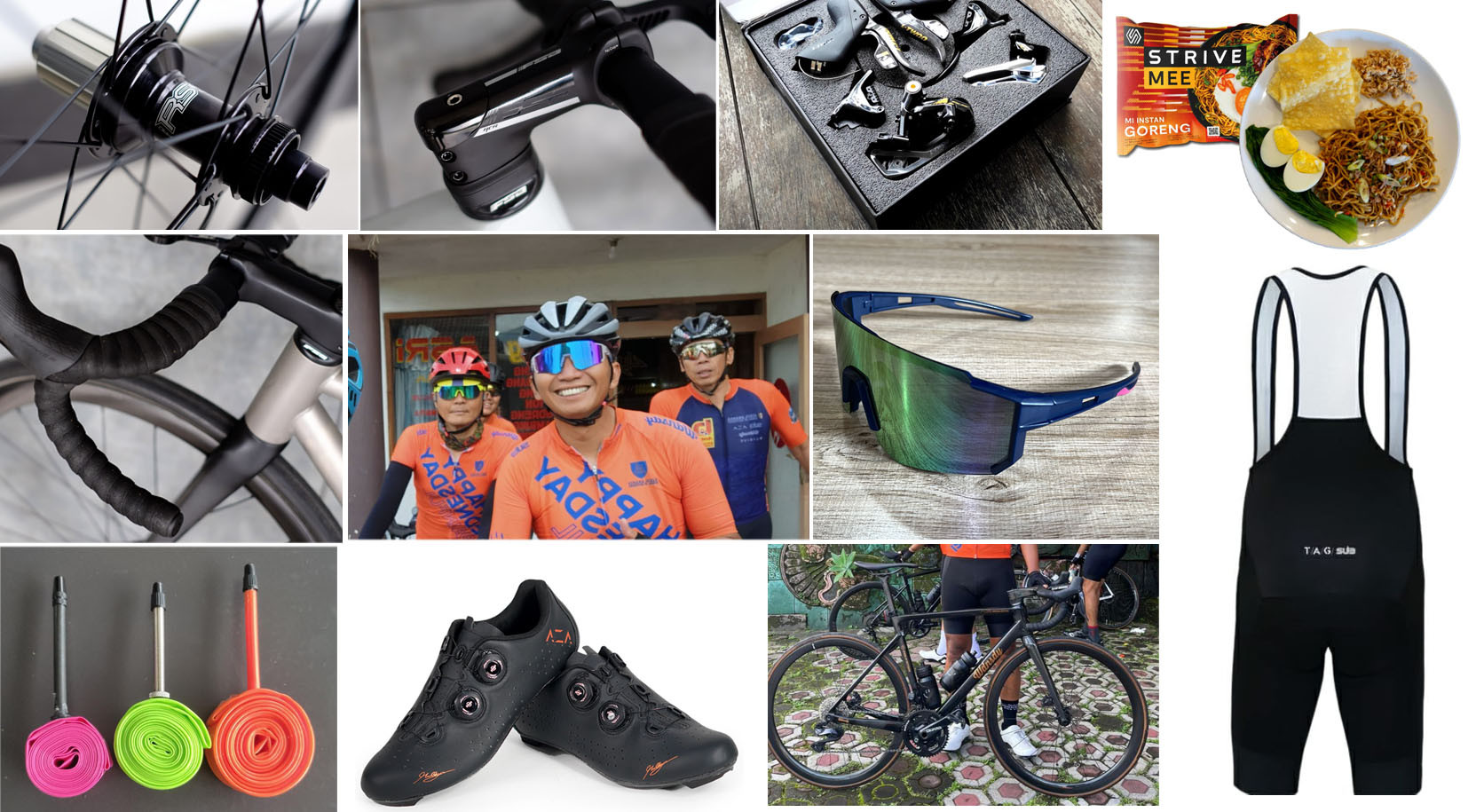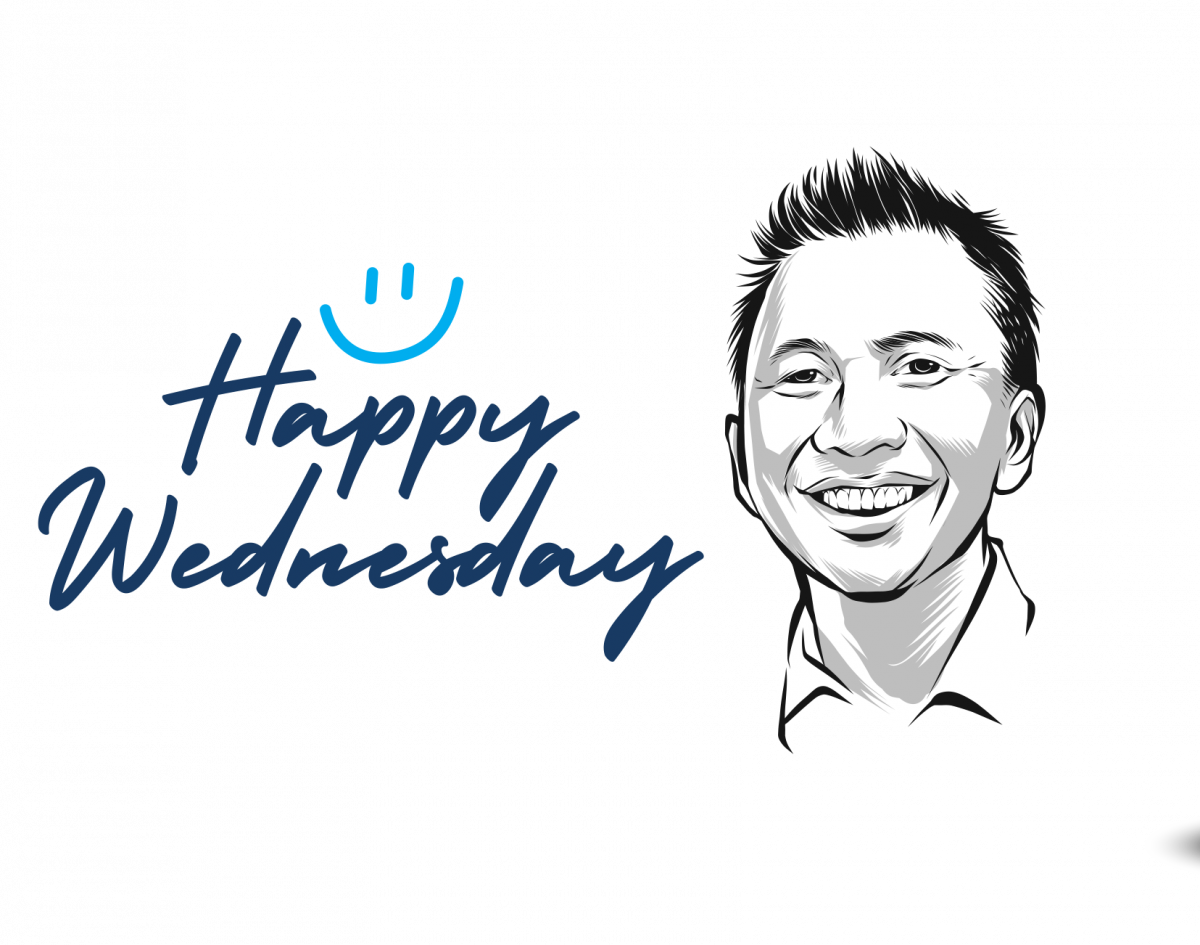“Fast food itu buruk!”
Sering saya mendengar itu. Orang mendoktrinasi yang lain dengan statement persis seperti itu. Tanpa mendalami makna harfiahnya, tanpa mengetahui latar belakang sejarahnya. Tanpa pula memperhatikan pembandingnya.
Kalau menurut ajaran profesor (dosen) filosofi bahasa saya waktu kuliah di Sacramento dulu, maka pernyataan “Fast food itu buruk” bisa termasuk sebuah logical fallacy. Termasuk sebuah asumsi. Dan “assume” itu buruk karena “Making an a** out of u and me” (membuat kamu dan saya terlihat bodoh).
Mengernyitkan dahi? Bagus!
Saya memang ingin tulisan ini mengajak Anda agak mengernyitkan dahi. Untuk bisa melihat sesuatu dari dua sisi yang berbeda, untuk bisa mengeluarkan pernyataan yang lebih punya dasar.
Contoh yang gampang, ya soal fast food.
Sebelum berlanjut, saya akan mengakui dari awal. Saya penggemar fast food. Saya menolak menyebutnya “fast food.” Saya suka menyebutnya dengan istilah “good food quickly.”
Saya suka Bic Mac dan Apple Pie di McDonald’s. Saya suka banget ayam original KFC. Saya sudah puluhan tahun memesan makanan yang sama kalau ke Burger King. Yaitu Whopper Junior with no pickle, onion, and tomato. Dan lain-lain.
Kalau sedang traveling juga sama. Wajib makan burger In-N-Out kalau di California. Atau merasakan burger-burger lokal di kota-kota lain. Menu resto waralaba lain yang saya suka: Monster taco di Jack in the Box, roast beef di Arby’s, plus sandwich di Subway dan lain-lain.
Pernah saya sedang road trip naik mobil di Amerika bersama Abah, dan berhenti di sebuah resto fast food di sisi highway untuk istirahat isi bensin (perut). Sebuah resto Jack in the Box.
“Kamu ini makannya beginian terus,” kata Abah, yang sangat disiplin dalam mengatur asupan pribadi.
Saya punya balasan yang sangat kuat: “Kalau tidak ada fast food, saya mungkin dulu tidak bisa menuntaskan kuliah. Kalau tidak ada fast food, akan ada masalah pangan di Amerika. Di sini, fast food tergolong ketahanan pangan.”
Seperti biasa. Kami berdiskusi soal ini. Saling tantang isi pikiran.
***
Banyak orang di Indonesia harus memahami ini: Di Amerika, negara empunya good food quickly, makanan jenis itu seperti warung pecel atau nasi Padang di Indonesia.
Kebanyakan wilayah Amerika tidak diberkahi sayur mayur dan buah-buahan seperti di Indonesia. Mereka lebih diberkahi sapi. Buah dan sayur mungkin impor, sapi pasti barang lokal. Sejak zaman warga asli Amerika, makanannya ya banyak daging.
Hamburger adalah nasi pecelnya Amerika. Bongkahan daging sapi cincang yang diapit dua roti bundar, dihiasi keju, lettuce, telur, tomat, atau “aksesori” lain. Plus kentang goreng.
Kalau di Jawa Timur kita ke kota-kota cari warung pecel yang enak, maka kalau di Amerika cari kedai burger yang enak. Dari daging cincang asli yang dimasak.
Kalau di “warung burger asli,” rasanya enak dan segar. Tiap kota pasti punya tempat seperti itu. Waktu mengunjungi Portland, Oregon, beberapa hari lalu, saya direkomendasikan pergi ke Super Deluxe Burger. Sebuah warung lokal yang menjual burger menggunakan bahan-bahan dari wilayah setempat.
Semuanya praktis dan bisa disajikan dengan cepat. Banyak yang benar-benar menggunakan daging cincang segar, dengan sayur segar, tomat segar, kentang segar, dan lain-lain.
Fast? Ya. Tidak sehat? Belum tentu! Bisa segar dan sehat!
Good food quickly jadinya.
Yang waralaba memang agak beda. Mereka harus mempersiapkan bahan baku dengan cara beda, supaya bisa menyajikan dengan skala massive, konsisten, dan cepat. Enak? Ya. Segar? Mungkin tidak. Tapi juga belum tentu tidak sehat.
Harga? Nah ini kunci utamanya.
***
Sama seperti di Indonesia, kebanyakan warga Amerika tidak mampu makan di restoran setiap hari. Apalagi tiga kali sehari. Malah, di Amerika, masak di rumah bisa lebih mahal daripada di restoran cepat saji. Belum lagi waktu yang habis karena harus menyiapkan makanan, sementara di rumah tidak mungkin punya pembantu, apalagi juru masak.
Waralaba cepat saji merupakan “penemuan” untuk memenuhi kebutuhan warga di sana. Menyediakan makanan enak dan cepat untuk barisan pekerja di Amerika.
Waktu makan bersama Abah di Jack in the Box itu, saya menunjukkan sekeliling. Bahwa yang makan di situ adalah orang-orang blue collar (kalangan pekerja). Seperti pekerja konstruksi, sopir truk, dan lain-lain.
Karena itu saya tegaskan: Fast food adalah ketahanan pangan. Tidak ada fast food di Amerika sama seperti tidak ada warteg atau warung pecel di Indonesia.
Lalu saya cerita, waktu kuliah dulu, saya harus berterima kasih kepada McDonald’s dan KFC dan fast food lain.
Mungkin ada yang pernah baca tulisan saya, kalau saya dulu kuliah pas terjadinya krisis moneter (1995-1999). Orang tua belum kaya, sehingga saya harus bekerja jadi pelayan kafetaria dan barista.
Gaji waktu itu: USD 5.75 per jam. Sesuai upah minimum resmi. Kerja maksimal 20 jam seminggu karena saya berstatus pelajar perguruan tinggi part time. Itu berarti, saya dapat bayaran hanya USD 115 seminggu, atau USD 460 sebulan. Dibayar setiap dua minggu, dipotong biaya administrasi/pajak setiap mendapatkan cek gaji.
Semuanya sangat kurang untuk bayar tempat tinggal, bahan bakar mobil, asuransi mobil, listrik, air, dan lain-lain. Apalagi untuk tuntutan kebahagiaan hidup anak muda (jalan-jalan, pacaran, dan lain-lain).
Uang tambahan saya dapatkan dari mengerjakan tugas teman (USD 50-250 per naskah), menjoki kelas teman (bisa USD 2.000 per semester pendek, he he he). Juga jual beli barang mainan koleksi di eBay.
Untuk hemat biaya, saya dan tiga orang teman sewa rumah bersama. Untuk menghemat biaya makan, kami saling menunjang. Kebetulan, tiga dari kami bekerja di restoran. Saya kerja di kafetaria kampus, ada yang kerja di resto pizza, ada yang di chinese restaurant.
Kami bergantian membawakan makanan dari tempat kerja masing-masing. Bisa makanan yang tersisa, atau makanan yang tidak ketahuan kami bawa (he he).
Kalau makan ke luar, ya harus ke fast food. Kalau makan di resto biasa, minimal harus keluar USD 7-10 per orang. Itu minimal, dan itu resto biasa. Sama sekali tidak mewah. Makan di food court mal juga segituan. Plus harus bayar tip, nilainya 10-20 persen dari total harga makanan.
Karena tidak ada warung pecel atau warteg, ya memang harus ke fast food. Murah sekali. Kebetulan di kampus ada Burger King. Satu Whopper Junior waktu itu harganya hanya USD 1 (ya, hanya satu dollar).
McDonald’s juga murah abis. Cukup membayar USD 3,22 (ya, 3 dollar dan 22 sen), sudah dapat paket Big Mac, kentang, dan minuman.
Paling bahagia waktu ada masa-masa promo. Misalnya promo Minggu dan Rabu di McDonald’s.
Kalau Minggu, satu cheeseburger hanya 29 sen.
Kalau Rabu, satu beefburger hanya 19 sen.
Setiap orang maksimal membeli 15 buah.
Kami pun antre, masing-masing beli 15. Bisa terkumpul 60 potong setiap hari promo. Kami bawa pulang, lalu disimpan di kulkas. Sehari itu, plus kadang beberapa hari selanjutnya, kami hanya makan itu (dipanasi di microwave).
Wkwkwkwk…
Bayangkan kalau dulu tidak ada fast food, hidup kami pasti sangat tidak bahagia. Sama dengan kalau di Indonesia tidak ada warung pinggir jalan…
***
Sampai hari ini pun, resto cepat saji tetap menjadi opsi termurah (dan tercepat). Tidak semurah zaman kuliah dulu, tapi tetap paling murah. Dan seiring perkembangan teknologi, kualitas bisa makin baik.
Karena itu, saya sering geleng-geleng kepala kalau ada orang Indonesia yang dengan ringan bilang “Fast food itu buruk.” Tanpa dilandasi penjelasan dan logika.
Dan saya paling sebal ketika ada yang menyebutnya “junk food.” Kalau itu sampah, ya jangan dimakan. Kok gampang sekali mengejek sesuatu sebagai sampah?
Kalau burger ayam KFC disebut “junk” alias sampah, lalu kerupuk “uyel” dan “upil” itu apa? Bagaimana dengan cimol, cireng, dan teman-temannya?
Ya, tentu saja, segalanya kalau kebanyakan pasti tidak baik. Makan nasi kebanyakan juga tidak baik. Daging kebanyakan tidak baik. Sayur melulu pun tidak baik. Kebanyakan gorengan tidak baik. Kebanyakan santan tidak baik. Cinta berlebihan juga bisa membuat kita buta.
Sebagai penggemar fast food, saya sekarang tetap mengimbanginya. Kan tidak setiap hari, tidak tiga kali sehari. Apalagi semakin tambah umur, semakin terasa kokefek barang yang dimasukkan ke dalam badan.
Dan saya mengimbanginya dengan aktivitas, dengan disiplin olahraga.
Seimbang. Balance. Sesuatu yang seharusnya kita kejar dalam segala hal bukan? Di dunia ini, tidak pernah ada hal ekstrem yang baik! (azrul ananda)
BONUS CERITA:
Impossible Kesulitan Penuhi Pasar
Rupanya, banyak pembaca doyan tulisan “daging sapi” Impossible saya di Happy Wednesday 21 lalu. Dan “daging” itu sekarang benar-benar bikin orang di Amerika penasaran.
Saya pergi ke beberapa tempat yang seharusnya menjual Impossible Burger, tapi banyak yang kehabisan dan bahkan tidak lagi menjualnya.
Impossible Foods, produsennya, memang sedang kesulitan memenuhi demand (permintaan pasar). Pabrik daging mereka di Oakland, California, benar-benar kerja keras memproduksi.
Selain itu, Burger King serius akan menyediakan menu ini di seluruh Amerika, dan itu menuntut volume produksi yang luar biasa.
Misi Impossible Foods untuk menantang peternakan kini berada di jalur yang mereka inginkan. “Daging” mereka disukai orang, dan harganya setara dengan daging beneran. Bahkan ketika skala produksi sudah mencapai titik tertentu, bukan tidak mungkin harga bisa lebih murah.
Yang jadi pertanyaan, mampukah Impossible Foods terus melaju di jalan itu?