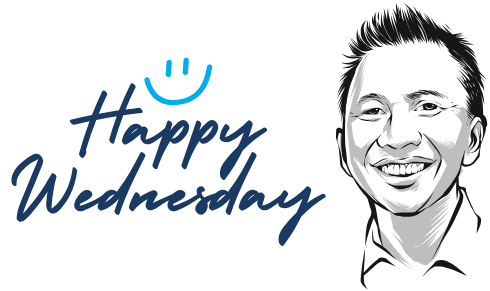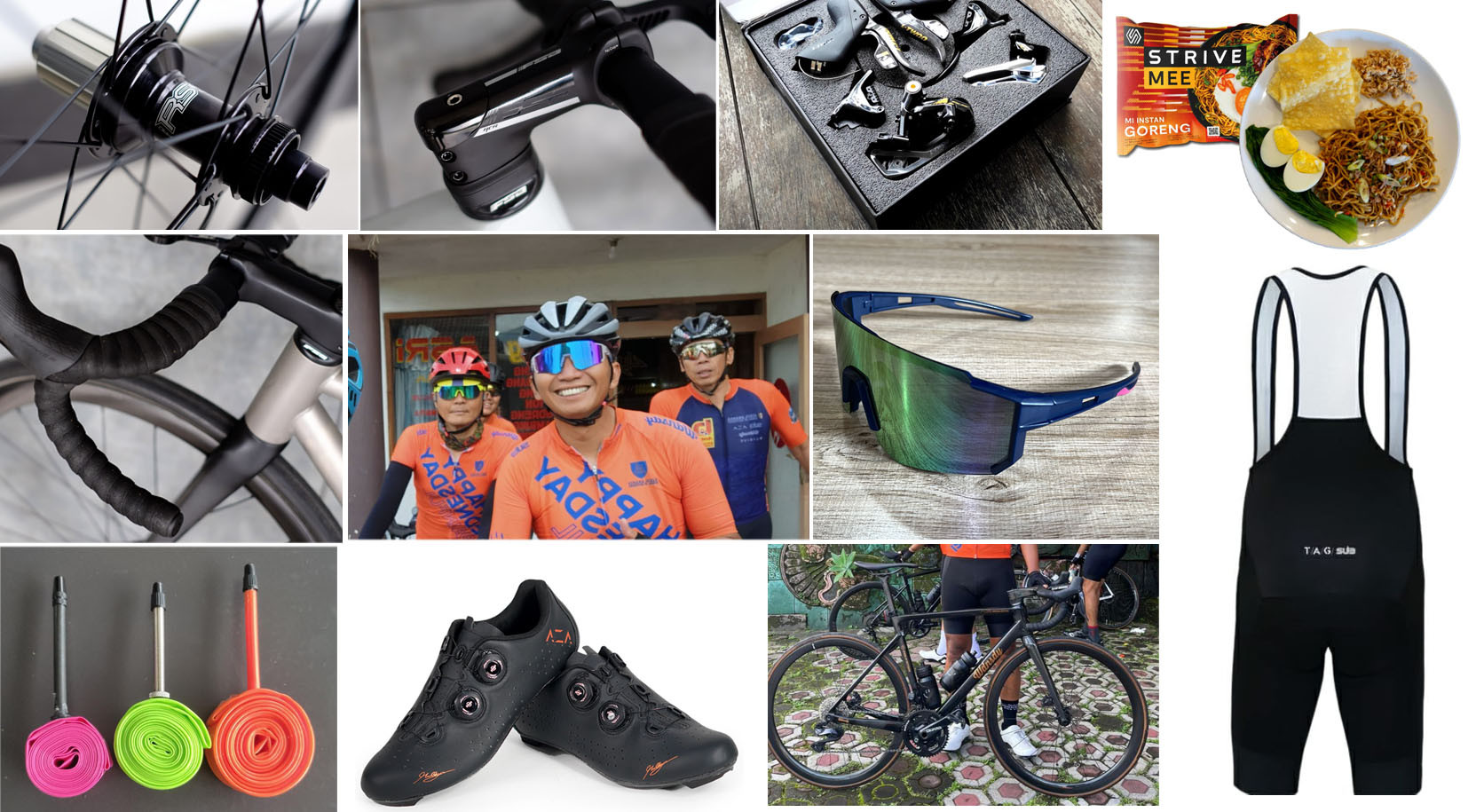Marc Marquez merayakan gelar juara dunianya yang ke-8 di GP Thailand 2019 dengan membawa bola biliar raksasa (Foto: AP)
Sebagai penggemar motorsport, tontonan saya sudah hampir habis tahun ini. Formula 1 hanya menyisakan satu lomba di Abu Dhabi, MotoGP sudah tuntas-tas. Keduanya sudah punya champion. Lewis Hamilton dan Marc Marquez. Sama-sama pemecah dan pemegang rekor, sekaligus sama-sama pemburu rekor. Secara statistik, sama-sama calon tersukses dalam sejarah.
Sebagai mantan pengamat dan komentator balap, keduanya sering membuat saya berpikir. Apakah keduanya benar-benar true champion, atau jadi champion karena secara sikon diuntungkan, selalu mendapatkan equipment terbaik?
Marc Marquez misalnya. Masuk kelas tertinggi (MotoGP) pada 2013, langsung juara dunia. Lalu terus jadi juara dunia hingga 2019, hanya gagal pada 2015. Total enam kali world champion dari tujuh musim.
Tahun 2019 ini pecah rekor poin terbanyak, 420 poin, setelah memenangi 12 dari 19 lomba, naik podium 18 kali dari 19 lomba.
Yang “mengerikan,” dia masih berusia 26 tahun. Kalau segalanya lancar, karirnya masih sangat panjang. Sulit dibayangkan seberapa hebat karirnya lima tahun lagi, atau bahkan 14 tahun lagi saat dia seumuran Valentino Rossi sekarang.
Mungkin, hanya waktu yang menghalangi Marquez menjadi pembalap terbaik dalam sejarah (minimal secara statistik).
Yang jadi pertanyaan, apakah dia akan diakui oleh semua sebagai pembalap terbaik dalam sejarah? Mengingat sejak masuk kelas tertinggi dia hampir selalu memiliki equipment terbaik?
Segala argumen bisa disampaikan di sini. Ya, dia selalu bersama Repsol Honda, yang begitu konsisten kuatnya. Tapi, di sisi lain, dia tidak sendirian naik Repsol Honda, dan pembalap lain tidak mampu sesukses dia. Lihat Jorge Lorenzo tahun ini. Lorenzo juga juara dunia gila, dan dia ampun-ampun mengejar hasil.
Entah mengapa, saya sendiri bukan penggemar berat Marquez. Salah satunya mungkin juga karena jalur karirnya “lebih mulus” dari kebanyakan. Saya juga bukan penggemar berat Valentino Rossi, karena awal karirnya dulu juga saya anggap agak mulus. Dan mungkin juga karena dia sekarang agak “overstay.”
Dari dulu, saya memang termasuk menyukai champion yang struggle lebih dulu. Saya jatuh cinta pada grand prix motor gara-gara Mick Doohan.
Generasi sekarang mungkin tidak kenal Doohan itu siapa, walau pada 1990-an dia pernah balapan dan menang di Sirkuit Sentul. Waktu Indonesia masih jadi tuan rumah grand prix (waktu itu 500, 250, dan 125 cc).
Doohan memang sempat sangat dominan. Menang gelar 500 cc (sekarang MotoGP) lima tahun berturut-turut antara 1994 hingga 1998. Sama, naik motor factory Honda. Pada 1997 dia juga dominan luar biasa, menang 12 dari 15 lomba.
Tapi, di balik sukses itu, penggemarnya merasakan “penderitaan” seorang Doohan mengejar juara. Khususnya pada 1992, di saat dia seharusnya dominan menunggangi Rothmans-Honda (posternya ada di dinding kamar saya dulu).
 Mick Doohan ketika masih membela Rothmans-Honda
Mick Doohan ketika masih membela Rothmans-Honda
Doohan mendominasi awal musim, memimpin klasemen sejauh 65 poin. Kemudian dia mengalami kecelakaan mengerikan di Dutch TT. Kaki kanannya hancur, terancam diamputasi. Delapan minggu lamanya dia absen. Di akhir musim, dia mencoba comeback mengamankan gelar. Namun, pada akhirnya harus rela kalah hanya empat poin dari Wayne Rainey.
Semua penggemar balap memberikan aplaus dan mengagumi perjuangan Doohan waktu itu.
Pada 1993, dia masih belum 100 persen. Kaki kanannya masih belum berfungsi normal. Bahkan untuk rem belakang dia harus menggunakan jempol tangan kiri, karena engkel kanannya tidak bisa “digunakan.”
Ketika akhirnya cukup pulih, mulai 1994 hingga 1998 Doohan menguasai dunia balap motor.
Saya kali pertama bertemu pembalap Australia itu pada 2001, saat meliput Grand Prix Australia (F1). Alangkah bahagianya waktu itu, bertemu dengan tokoh idola.
 Azrul Ananda bersama Mick Doohan (kiri) dan Barry Sheene, GP Australia 2001
Azrul Ananda bersama Mick Doohan (kiri) dan Barry Sheene, GP Australia 2001
Secara statistik, Doohan akan jauh kalah dari seorang Marquez. Juga mungkin tidak akan sepopuler Marquez. Tapi bagi saya akan selalu punya nilai tambah: Seorang champion yang sudah teruji oleh siksaan dan rasa sakit luar biasa…
***
Beralih ke Formula 1, Lewis Hamilton telah mengunci gelar keenam dalam karirnya. Satu kali lagi, maka dia akan menyamai rekor tujuh gelar champion seorang Michael Schumacher. Hamilton juga sudah memenangi total 83 lomba (hingga GP Brazil 2019), hanya delapan lebih sedikit dari Michael Schumacher. Dia sudah naik podium 150 kali, hanya lima lebih sedikit dari Michael Schumacher.
Beberapa rekor sudah direbut oleh Hamilton. Misalnya, pole position terbanyak (87 kali), dan poin terbanyak (3.405).
Dengan usia 34 tahun, Hamilton memang sudah tidak lagi muda. Namun di arena F1, dia juga belum bisa dibilang tua. Kalau lancar, dengan mudah dia masih bisa berkiprah minimal lima tahun lagi. Sangat cukup waktu untuk mengejar dan menyalip segala rekor Michael Schumacher.
Schumacher misalnya, walau sempat pensiun dan come back, terus membalap sampai usia 40-an. Total menjalani 308 grand prix. Hamilton “baru” menjalani 249 lomba. Masih cukup banyak waktu.
Di akhir karirnya nanti, Hamilton punya kans jadi pembalap terbaik dalam sejarah. Minimal secara statistik.
Lagi-lagi, saya beruntung pernah jadi saksi sejarah. Saya berada di Melbourne saat Hamilton menjalani debutnya di Grand Prix Australia 2007. Dia masih “anak-anak,” saya masih lebih muda dari sekarang.
 Azrul Ananda bersama Lewis Hamilton, GP Australia 2007
Azrul Ananda bersama Lewis Hamilton, GP Australia 2007
Waktu itu, banyak yang sudah merasa kalau Hamilton adalah “the chosen one.” Anak ajaib yang akan merajai F1.
Meski demikian, tahun-tahun pertama karir Hamilton tidaklah semulus harapan. Tim McLaren-Mercedes sangat kuat, namun bukanlah kekuatan dominan. Belum lagi persaingan internal yang panas antara Hamilton dan Fernando Alonso.
Antara 2007 hingga 2012, Hamilton hanya menjadi juara dunia sekali bersama McLaren. Ketika dia membuat keputusan besar pindah ke Mercedes pada 2013, banyak yang merasa itu bukan keputusan tepat.
Seorang pembalap yang “the chosen one” mungkin tidak akan menghasilkan karir super cemerlang.
Antara 2014 hingga 2019, Hamilton membungkam semua kritik. Ya, Mercedes mampu mendominasi di era hybrid (menurut saya, era mesin suara bemo). Tapi Hamilton tetap harus mengeksekusinya dengan sempurna. Selama enam tahun terakhir, Hamilton hanya “kalah” sekali dari rekan setimnya, Nico Rosberg. Pada 2016.
Di penghujung 2016 itu, Rosberg langsung pensiun. Menegaskan betapa beratnya upaya fisik dan mental untuk jadi seorang juara dunia. Dia memilih meninggalkan F1, hidup nyaman bersama keluarga, daripada harus menjalaninya lagi.
Hamilton, tentu saja, terus tancap gas. Relatif tanpa pesaing lagi hingga 2019 ini. Belakangan, mobilnya tidak selalu jadi yang terbaik. Tapi Hamilton selalu siap “menerkam” kemenangan setiap kali ada kesempatan. Misalnya saat lawan melemah atau membuat kesalahan.
Usai mengamankan gelar juara dunia keenamnya di Amerika Serikat, Hamilton menegaskan niatan untuk terus memburu gelar tertinggi. Dia benar-benar ingin meninggalkan jejak istimewa.
“Kita semua harus selalu menantang diri sendiri untuk menciptakan mahakarya dalam segala bentuk. Karya saya belum berakhir,” tegasnya.
Dengan karir seperti itu, yang tidak “semulus” Marquez, saya pribadi menjadi lebih “tengah-tengah” dalam mengagumi Hamilton. Dia sudah berjuang, dia seorang fighter, dan dia begitu konsisten.
Idola nomor satu saya di F1 tetap –dan akan selalu-- Ayrton Senna. Yang andai tidak tewas pada 1994 mungkin juga tidak akan sesukses Lewis Hamilton.
Kebetulan, Hamilton juga mengidolakan Senna. Itu nilai plus buat dia di mata saya, he he he…
Anyway, jadi apa kesimpulan dari tulisan ini? Baik itu Marquez, Rossi, Doohan, Hamilton, Schumacher, maupun Senna, semua punya kesamaan: Tidak mau mengalah dan siap menerkam segala kesempatan.
Lihat Marquez dan Hamilton tahun ini. Pada beberapa lomba, mereka sebenarnya finis kedua juga tidak apa-apa. Bahkan kalau mereka finis kedua, banyak penggemar mungkin senang. Karena itu memberi kesempatan untuk pembalap lain untuk meraih kemenangan (kasihan oh dikau Fabio Quartararo…).
Namun, mereka tidak peduli. Para champion ini selalu ingin menang. No mercy. Begitu ada celah, mereka akan ambil. Tidak ada rileks, tidak ada mengendur.
Selamat untuk Marc Marquez dan Lewis Hamilton, world champion MotoGP dan Formula 1 2019. Selamat mengejar masterpiece, memburu statistik terbaik dalam sejarah. Mereka sangat bisa, sangat mampu.(azrul ananda)
PS: Dalam hati kecil saya: Semoga tahun depan MotoGP dan Formula 1 berlangsung lebih seru. Bahkan, saya berharap ada juara baru. He he he…